Jakarta, 15 Oktober 2025 – Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dengan lebih dari 5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia pada awal 2024. Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap perilaku dan interaksi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Namun, meskipun semakin terhubung secara digital, Gen Z—sebagai generasi yang tumbuh besar bersama teknologi—malah menghadapi paradoks besar: mereka merasa semakin kesepian meski terus terhubung melalui platform sosial.
Menu sosial media yang terus berkembang menciptakan dunia baru dalam pemasaran digital. Para marketer kini tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana cara menciptakan hubungan emosional yang mendalam dengan audiens. Untuk itu, pemasaran harus mampu menjembatani jarak yang semakin lebar antara dunia digital yang efisien dan interaksi manusia yang penuh makna.
Gen Z: Terkoneksi Tapi Kesepian
Generasi Z, yang dikenal sangat melek digital, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di media sosial. Meski demikian, sebuah studi yang dilakukan oleh Appel dkk. (2019) menunjukkan fenomena yang cukup mengkhawatirkan: semakin banyak waktu yang dihabiskan di dunia maya, semakin besar pula rasa kesepian yang mereka rasakan. Menu interaksi di media sosial justru memperburuk kualitas hubungan mereka, dengan banyak Gen Z merasa kurang memiliki koneksi yang bermakna, meskipun mereka terhubung dengan ribuan orang.
Fenomena ini juga didukung oleh data dari Cigna (2018), yang menyebutkan bahwa Gen Z adalah generasi paling kesepian meskipun mereka adalah pengguna aktif media sosial. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dengan adanya tren curhat anonim di Twitter (X) atau TikTok, di mana banyak dari mereka mencari perhatian dan validasi sosial. Di sisi lain, para marketer kini harus beradaptasi dengan cara yang lebih personal dan emosional untuk mengatasi fenomena ini.
Marketing Influencer: Dari Selebriti ke Virtual Idola
Dalam dunia pemasaran, influencer telah menjadi kekuatan utama di media sosial. Di Indonesia, banyak brand—terutama yang bergerak di sektor kecantikan dan makanan—menggandeng micro-influencer yang memiliki pengikut lebih sedikit tetapi memiliki engagement yang lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya kedekatan emosional yang dibangun oleh para influencer dengan audiens mereka.
Namun, paradoks muncul saat semakin banyak influencer yang muncul, tingkat kepercayaan publik justru menurun. Banyak audiens yang mulai sadar bahwa banyak konten yang mereka lihat sebenarnya adalah sponsor. Sebagai contoh, Menu influencer kini tidak hanya terdiri dari selebritas, tetapi juga avatar digital yang disebut virtual influencer seperti Lil Miquela, yang mulai populer di TikTok. Meskipun mereka tidak nyata, virtual influencer ini mampu menciptakan interaksi yang lebih personal dengan audiens mereka, meskipun terkadang terasa lebih jauh dan kurang autentik.
AI dalam Media Sosial: Keefisienan Tanpa Sentuhan Manusia
Menghadapi tren ini, AI (artificial intelligence) mulai memainkan peran yang lebih besar dalam dunia media sosial. Dari chatbot layanan pelanggan hingga sistem rekomendasi berbasis algoritma, AI semakin canggih dalam mempercepat dan mempermudah interaksi antara brand dan audiens. Menu pemasaran yang lebih terotomatisasi ini menawarkan efisiensi yang luar biasa, tetapi paradoksnya, interaksi yang lebih cepat juga seringkali terasa lebih dingin dan kurang emosional.
Misalnya, e-commerce menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan dasar pelanggan, atau platform seperti Sephora yang menggunakan AI untuk membantu pelanggan menemukan produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Walaupun efisien, interaksi yang dilakukan oleh AI ini seringkali tidak mampu menggantikan sentuhan manusia, yang dibutuhkan untuk menciptakan hubungan yang lebih emosional dan bermakna.
Menghadapi Paradoks Media Sosial dalam Pemasaran
Bagi para pemasar, tantangan besar terletak pada bagaimana menemukan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi canggih seperti AI dan tetap menjaga hubungan yang hangat dan emosional dengan audiens. Menu pemasaran yang hanya bergantung pada algoritma dan influencer digital mungkin berhasil dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, hubungan yang dibangun tanpa kedekatan emosional akan kehilangan maknanya.
Pemasaran yang sukses di era digital ini tidak hanya tentang meningkatkan angka likes atau followers, tetapi juga tentang menciptakan komunitas yang solid dengan interaksi yang lebih otentik dan bermakna. Bagi Gen Z, yang kini tengah berjuang dengan rasa kesepian di dunia maya, brand yang mampu menghadirkan human-touch di tengah teknologi yang semakin otomatis akan lebih dipercaya dan dihargai.
Kesimpulan: Teknologi dan Empati dalam Marketing
Paradoks yang muncul di dunia media sosial, seperti kesepian meski terkoneksi, penurunan kepercayaan pada influencer, dan interaksi yang dingin karena AI, menuntut para pemasar untuk lebih kreatif dalam membangun hubungan yang lebih autentik dengan audiens. Menu pemasaran yang efektif di masa depan adalah yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat koneksi emosional, bukan sekadar efisiensi. Sebagai pengingat, prinsip Marketing 5.0 yang mengatakan, “Machine is Cool, Human is Warm,” menjadi kunci untuk menyeimbangkan kecepatan dan kedalaman dalam dunia pemasaran digital yang semakin maju.



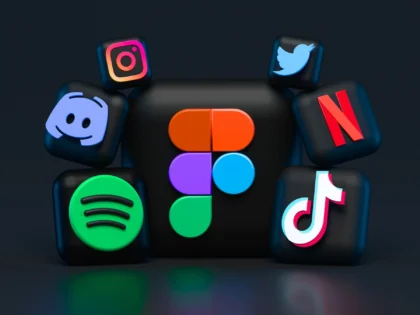












Komentar